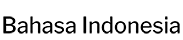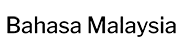Korban Bom Bali yang Terlupakan
2016.05.20
Jakarta
 Chusnul Chotimah (kiri) bersama putranya, Musoffa Adha, di rumah mereka di Sidoarjo, Jawa Timur, 15 Mei 2016.
Chusnul Chotimah (kiri) bersama putranya, Musoffa Adha, di rumah mereka di Sidoarjo, Jawa Timur, 15 Mei 2016.
Chusnul Chotimah sedang berjalan ke arah Rumah Makan Padang yang terletak di salah satu sudut kawasan Kuta, Bali, 14 tahun lalu. Kedatangan sepasang suami istri yang kawan dekat keluarga, memaksanya membeli makan malam untuk mereka.
Ditemani tamunya, Wati, kedua perempuan ini memesan makanan. Sang suami, Dwi Boedy Santoso, sempat melarang Chusnul keluar rumah sebab sudah agak larut. Tapi, Jalan Legian masih ramai lalu lalang wisatawan karena malam Minggu.
“Bapak merasa ragu untuk menyuruh ibu. Tapi namanya ada tamu di rumah, kalau tak dijamu kurang pas rasanya,” ujar Musoffa Adha (24), anak kedua pasangan Dwi-Chusnul, kepada BeritaBenar yang mewawancarainya via telepon, Senin, 16 Mei 2016.
Tiba-tiba guncangan kuat menghancurkan rumah makan itu, yang terletak sekitar 100 meter dari Paddy’s Pub. Hampir bersamaan, satu ledakan lain dari Sari Club tak kalah dahsyatnya. Tercatat 202 orang tewas dan 209 lainnya luka-luka dalam serangan bom pada 12 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, kelompok jaringan al-Qaeda di Asia Tenggara.
Tubuh Chusnul dan Wati terpental beberapa meter. Chusnul pingsan. Saat membuka mata, dia menyaksikan orang-orang berlarian, sementara di sekitarnya hancur. Dia mengaku melihat seorang bule lari dengan potongan kaca tertancap di matanya.
Chusnul pun mengecek tubuhnya sendiri; penuh luka bakar, pecahan kaca tertancap di kaki, dan tak ada sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Dia berteriak minta tolong. Bersama para korban lain, dia dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Sanglah, Denpasar.
Mengetahui ada ledakan bom, Dwi segera mendatangi lokasi, menerobos garis pembatas polisi, mencari istrinya. Dia membuka kantong mayat satu per satu. Dwi tak menemukan istrinya.
“Mayat-mayat terbakar menyerupai arang,” tutur Musoffa menirukan cerita ayahnya.
Dwi akhirnya menemukan sang istri yang terluka parah di RS Sanglah. Serangan itu juga melukai Wati. Perempuan itu cacat seumur hidup akibat luka bakar.
Tak dapat bantuan pemerintah
Chusnul menerima tawaran operasi dari Pemerintah Australia. Ditemani sang suami, dia terbang seminggu setelah serangan teroris itu.
“Ibu dioperasi plastik di Australia dengan menyayat kulit paha untuk menutup luka di muka dan kedua lengannya,” jelas Musoffa.
Keberangkatan mereka ke Australia mendatangkan cerita pahit. Rekan bisnis Dwi yang diminta tolong menjaga rumah, kabur membawa modal dan sepeda motor.
Chusnul juga tidak mendapatkan bantuan Rp. 20 juta per korban dari pemerintah yang dititipkan melalui RS Sanglah.
“Kemana uang yang seharusnya buat ibu saya? Ketika bapak bertanya bantuan, pihak rumah sakit berdalih tidak tahu,” tutur Musoffa.
Akhirnya, Dwi dan Chusnul memutuskan pulang ke Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menjalani hari-hari lebih berat. Pasangan suami istri yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang sablon baju di Kuta harus menjalani kehidupan lain.
“Ibu bekerja sebagai penjual sayur keliling dan bapak menjadi buruh. Ibu berangkat jam 1 malam untuk beli bahan dan pulang jam 9 pagi setelah menjajakan sayur,” jelas Musoffa.
Jengah dengan ulah netizen
Kuliah Musoffa terhenti karena tak ada biaya. “Saya jadi juri burung gantangan. Saya buka usaha kerajinan kayu kecil-kecilan,” tuturnya.
Tak hanya himpitan ekonomi, cibiran warga menambah penderitaan keluarga ini. Chusnul sering disalahkan hanya karena dia dan suaminya bekerja di Bali.
“Banyak teman saya menyalahkan ibu karena bekerja di pulau hiburan Bali padahal ibu saya bekerja secara halal demi kami anak-anaknya,” tutur Musoffa.
Musoffa mengaku jengah dengan ulah netizen yang menggaungkan “Kami Tidak Takut” usai penembakan di Jalan Thamrin, Jakarta, awal tahun ini. Dalam serangan itu, empat warga dan empat pelaku tewas serta sejumlah lainnya luka-luka.
“Mungkin bagi mereka, ini lelucon atau bentuk perlawanan. Mereka tidak tahu betapa ngeri dampak serangan teroris. Bayangkan jika perkataan itu memicu gerakan teroris, yang berani mati membom kota-kota besar secara serentak,” ujar Musoffa.
Meski sudah dioperasi, Musoffa mengatakan masih ada sisa material di kaki ibunya. Untuk itu, ia menggalang dana lewat laman KitaBisa.com dan pesan berantai. Hanya saja hasilnya jauh dari harapan.
“Tujuannya agar bisa operasi ibu, karena kaki ibu sering ngilu. Jika ada sisa nanti dipakai ibu untuk membuka warung. Biar beliau nggak perlu jualan sayur keliling lagi,” harap Musoffa.
Tidak ada lembaga khusus
Oscar Primadi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dikonfirmasi BeritaBenar, Jumat, 20 Mei 2016, mengaku belum mendapat informasi tentang korban bom Bali membutuhkan penanganan medis. Meski berjanji akan mengecek, Oscar menegaskan untuk pembiayaan pemerintah sudah ditangani layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan, Ahmad Yunianto, menyatakan tidak ada lembaga khusus yang menangani korban serangan teroris. “Semestinya ini ranah Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Pemerintah Daerah masing-masing, apalagi dalam konteks per individu dan penanganan yang bertahun-tahun,” katanya.
Dwi Welasih, aktivis Yayasan Penyintas Indonesia (YPI) yang juga korban selamat aksi bom JW Marriot 2003 di Jakarta menyatakan prihatin dengan kondisi korban serangan teroris seperti dialami Chusnul.
“Saya pribadi sedih karena tidak bisa bantu apa-apa. YPI sudah coba lewat LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) tapi sampai kini masih terbentur prosedural yang berbelit-belit, sehingga tidak kunjung datang bantuan ke korban,” katanya kepada BeritaBenar.
“Bukan hanya Bu Chusnul, korban lain juga masih banyak membutuhkan pengobatan. Kita sudah coba ke Menteri Kesehatan, namun tidak direspons juga,” tambahnya.

Chusnul menyiapkan sayur-sayuran yang akan dijual berkeliling dengan sepeda motor, di rumahnya di Sidoarjo, 14 Mei 2016. (Dok. Keluarga)
Sering dicemooh
Bagi Chusnul, penderitaan seakan tak berhenti usai kejadian yang mengubah kehidupannya. "Saya menderita luka bakar 60 persen. Wajah dan tubuh saya penuh luka,” katanya kepada BeritaBenar.
Sepulang dari Australia, Yayasan Bali HD sempat membiayai pengobatanya. Tapi hanya bertahan dua tahun karena akhirnya yayasan itu tutup akibat kehabisan biaya.
Saat menjajakan sayur, Chusnul mengaku sering dicemooh. Suatu hari, saat masuk sebuah warung di Sidoarjo, orang-orang melihat ke arahnya dan bertanya apa yang terjadi.
“Saya bilang saya korban kena bom. Tapi mereka menertawakan saya sambil berujar, ‘Ibu kalau jawab yang benar! Mana ada bom di sini’,” ungkapnya meniru ucapan orang itu.
Dia mengaku terjerat utang ke rentenir. Familinya tidak mau lagi meminjamkan uang untuk biaya berobat. “Utang saya sekarang sudah mencapai Rp128 juta,” tuturnya menahan tangis.
Dia berharap pemerintah mau mendengarkan keluhannya. Chusnul tiga kali menulis surat ke Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Surat terakhir Januari 2015 lalu, ditanggapi. Seseorang yang mengaku dari Sekretariat Negara menghubunginya, berjanji akan membantu.
“Nyatanya sampai sekarang bantuan itu tidak ada,” ujarnya, “apa saya harus ke Jakarta dan tidur di depan Istana untuk menarik perhatian presiden? Jika pemerintah tidak mau bantu, saya minta disuntik mati saja. Saya tak kuat lagi hidup seperti ini.”